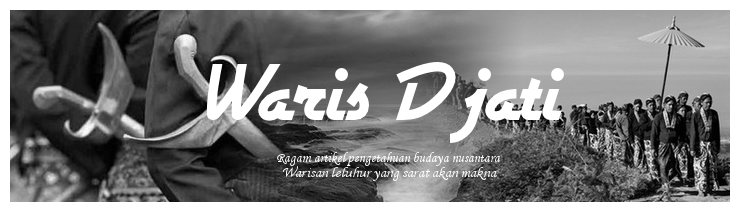Habib Muhammad bin Ali bin Hasan Bin Yahya (Pangeran Noto Igomo) mempunyai seorang sahabat dekat di Barabai. Namanya Habib Alwi bin Abdullah AlHabsyi. Keduanya mempunyai kedudukan terhormat di wilayahnya masing-masing. Habib Muhammad tinggal di Tenggarong selaku penasihat Sultan Kutai, sementara Habib Alwi adalah seorang Kapten Arab berkedudukan di Barabai. Mereka sudah saling mengenal sejak sama-sama tinggal di Hadramaut, Yaman.
Habib Alwi AlHabsyi, sejak di Hadramaut, mengakui keluasan pengetahuan dan kealiman Habib Muhammad Bin Yahya. Habib Muhammad kelahiran tahun 1844, sedangkan Habib Alwi beberapa tahun lebih muda. Tidak diketahui persis tahun kelahiran Habib Alwi.
"Tahun 1917-an, Habib Alwi di Banjar sudah mempunyai 3 anak," ujar Habib Agil bin Salim Bahsin, cucu Habib Alwi.
Jika Habib Muhammad Bin Yahya melalui perjalanan panjang melalui Palembang, Cirebon , Martapura dan akhirnya menetap di Kutai, maka Habib Alwi dari Hadramaut memilih Barabai sebagai tempat tinggal tetap setelah sempat bermukim beberapa tahun di Banjarmasin.
Habib Alwi menikah pertama kali di Banjarmasin dengan Syarifah Raguan binti Syekh AlHabsyi. Dengan istrinya Habib Alwi masih bersaudara dekat karena mereka sama-sama cucu dari Habib Alwi bin Syekh Al-Habsyi.
Ketika tinggal di Banjarmasin, Habib Alwi adalah pejabat Kapten Arab pengganti Habib Hasan bin Iderus Al Habsyi (Habib Ujung Murung). Habib Alwi tinggal di kawasan Ujung Murung.
Habib Alwi pindah ke Barabai setelah menikah di sana dengan seorang perempuan asal Nagara Banua Kupang bernama Hj Masrah. Belakangan Habib Alwi juga menikah dengan perempuan Kandangan bernama Masja.
Sejak melepaskan kedudukan sebagai Kapten Arab, Habib Alwi berdomisili di Barabai. Namun masyarakat tetap memperlakukannya sebagai orang istimewa karena latar belakang dan jasanya.
Jasa terbesar Habib Alwi bagi daerah Hulu Sungai adalah kepeloporan beliau dalam membangun perkebunan karet secara besar-besaran di Barabai. Habib Alwi memiliki kebun karet di Desa Manggasan, Hantakan, Barabai. Bibit karet diperoleh Habib Alwi dari Bogor melalui perantaraan pemerintah Belanda.
Walau tinggal di daerah berbeda dan dipisahkan jarak cukup jauh persahabatan Habib Alwi dan Habib Muhammad tetap terjalin mesra. Habib Muhammad yang menyumbang batu dan semen ketika Habib Alwi membangun Pasar Batu," ujar Ami Agil, panggilan sehari-hari Habib Agil bin Salim Bahsin.
Pasar Batu adalah bangunan beton pertama di Hulu Sungai yang merupakan tempat pasar gatah (karet) di paruh pertama abad lalu. Suatu masa kedua sahabat ini bertemu di Samarinda. Dalam pertemuan antara dua sahabat itu mereka tak lupa berfoto bersama dengan gaya masing-masing. Habib Muhammad mengenakan sarung dan baju koko berwarna putih, sementara Habib Alwi memakai busana baju safari dan celana panjang. Persamaan mereka adalah kopiah yang dikenakan serta masing-masing memakai tongkat.
Habib Muhammad masuk ke lingkungan Kesultanan Kutai berkat kelebihan dan kekuatan spiritualnya. Habib Muhammad Bin Yahya yang juga datuk dari aktor terkenal drg Fadly ini masuk ke istana setelah berhasil menyembuhkan penyakit seorang kerabat kesultanan.
Tak lama setelah kejadian itu, Habib Muhammad dinikahkan dengan Aji Raden Lesminingpuri, cucu Sultan AM Sulaiman yang juga anak Sultan AM Alimuddin.
Sedang, Habib Alwi sendiri juga menjadi tokoh kehormatan masyarakat Hulu Sungai terutama Barabai. Ketika Presiden Soekarno berkunjung wilayah Hulu Sunggai dan mampir ke Barabai tahun 1955, terjadi dialog singkat antara Habib Alwi dengan Sang Presiden.
Waktu berjabat tangan, disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya mereka berbincang-bincang.
"Siapa nama Pak Haji?" ujar Bung Karno.
“Saya Sayyid Alwi," jawab Habib Alwi.
"Pak Sayyid orang Arab?"
"Ya, saya orang Arab, lahir di Hadramaut."
"Mengapa orang Arab mau membantu perjuangan orang Indonesia ?"
"Saya muslim, dia juga orang muslim. Jadi wajib membantu. Ikhwanul muslimin (persaudaraan sesama orang Islam)."
"Pergi ke Jakarta nanti," Bung Karno menawarkan undangan kepada Habib Alwi.
"Ya, Batavia ." (seorang wedana di Hulu Sungai kemudian membisiki Habib Alwi bahwa yang benar adalahJakarta ).
"Yakarta," ujar Habib Alwi lagi mengoreksi ucapannya (Habib Alwi menyebut J dengan lafal Y).
Akhir cerita, Habib Alwi tak pernah ke Jakarta mendatangi undangan Presiden pertama RI itu.
Habib Alwi Al-Habsyi meninggal dunia tahun 1967 waktu berada di Banjarmasin dan dimakamkan di Turbah Sungai Jingah. Sahabatnya, Habib Muhammad Bin Yahya mendahuluinya 20 tahun sebelum itu dan bermakam di pekuburan Kelambu Kuning, Kutai Tenggarong.
Habib Alwi AlHabsyi, sejak di Hadramaut, mengakui keluasan pengetahuan dan kealiman Habib Muhammad Bin Yahya. Habib Muhammad kelahiran tahun 1844, sedangkan Habib Alwi beberapa tahun lebih muda. Tidak diketahui persis tahun kelahiran Habib Alwi.
"Tahun 1917-an, Habib Alwi di Banjar sudah mempunyai 3 anak," ujar Habib Agil bin Salim Bahsin, cucu Habib Alwi.
Jika Habib Muhammad Bin Yahya melalui perjalanan panjang melalui Palembang, Cirebon , Martapura dan akhirnya menetap di Kutai, maka Habib Alwi dari Hadramaut memilih Barabai sebagai tempat tinggal tetap setelah sempat bermukim beberapa tahun di Banjarmasin.
Habib Alwi menikah pertama kali di Banjarmasin dengan Syarifah Raguan binti Syekh AlHabsyi. Dengan istrinya Habib Alwi masih bersaudara dekat karena mereka sama-sama cucu dari Habib Alwi bin Syekh Al-Habsyi.
Ketika tinggal di Banjarmasin, Habib Alwi adalah pejabat Kapten Arab pengganti Habib Hasan bin Iderus Al Habsyi (Habib Ujung Murung). Habib Alwi tinggal di kawasan Ujung Murung.
Habib Alwi pindah ke Barabai setelah menikah di sana dengan seorang perempuan asal Nagara Banua Kupang bernama Hj Masrah. Belakangan Habib Alwi juga menikah dengan perempuan Kandangan bernama Masja.
Sejak melepaskan kedudukan sebagai Kapten Arab, Habib Alwi berdomisili di Barabai. Namun masyarakat tetap memperlakukannya sebagai orang istimewa karena latar belakang dan jasanya.
Jasa terbesar Habib Alwi bagi daerah Hulu Sungai adalah kepeloporan beliau dalam membangun perkebunan karet secara besar-besaran di Barabai. Habib Alwi memiliki kebun karet di Desa Manggasan, Hantakan, Barabai. Bibit karet diperoleh Habib Alwi dari Bogor melalui perantaraan pemerintah Belanda.
Walau tinggal di daerah berbeda dan dipisahkan jarak cukup jauh persahabatan Habib Alwi dan Habib Muhammad tetap terjalin mesra. Habib Muhammad yang menyumbang batu dan semen ketika Habib Alwi membangun Pasar Batu," ujar Ami Agil, panggilan sehari-hari Habib Agil bin Salim Bahsin.
Pasar Batu adalah bangunan beton pertama di Hulu Sungai yang merupakan tempat pasar gatah (karet) di paruh pertama abad lalu. Suatu masa kedua sahabat ini bertemu di Samarinda. Dalam pertemuan antara dua sahabat itu mereka tak lupa berfoto bersama dengan gaya masing-masing. Habib Muhammad mengenakan sarung dan baju koko berwarna putih, sementara Habib Alwi memakai busana baju safari dan celana panjang. Persamaan mereka adalah kopiah yang dikenakan serta masing-masing memakai tongkat.
Habib Muhammad masuk ke lingkungan Kesultanan Kutai berkat kelebihan dan kekuatan spiritualnya. Habib Muhammad Bin Yahya yang juga datuk dari aktor terkenal drg Fadly ini masuk ke istana setelah berhasil menyembuhkan penyakit seorang kerabat kesultanan.
Tak lama setelah kejadian itu, Habib Muhammad dinikahkan dengan Aji Raden Lesminingpuri, cucu Sultan AM Sulaiman yang juga anak Sultan AM Alimuddin.
Sedang, Habib Alwi sendiri juga menjadi tokoh kehormatan masyarakat Hulu Sungai terutama Barabai. Ketika Presiden Soekarno berkunjung wilayah Hulu Sunggai dan mampir ke Barabai tahun 1955, terjadi dialog singkat antara Habib Alwi dengan Sang Presiden.
Waktu berjabat tangan, disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya mereka berbincang-bincang.
"Siapa nama Pak Haji?" ujar Bung Karno.
“Saya Sayyid Alwi," jawab Habib Alwi.
"Pak Sayyid orang Arab?"
"Ya, saya orang Arab, lahir di Hadramaut."
"Mengapa orang Arab mau membantu perjuangan orang Indonesia ?"
"Saya muslim, dia juga orang muslim. Jadi wajib membantu. Ikhwanul muslimin (persaudaraan sesama orang Islam)."
"Pergi ke Jakarta nanti," Bung Karno menawarkan undangan kepada Habib Alwi.
"Ya, Batavia ." (seorang wedana di Hulu Sungai kemudian membisiki Habib Alwi bahwa yang benar adalahJakarta ).
"Yakarta," ujar Habib Alwi lagi mengoreksi ucapannya (Habib Alwi menyebut J dengan lafal Y).
Akhir cerita, Habib Alwi tak pernah ke Jakarta mendatangi undangan Presiden pertama RI itu.
Habib Alwi Al-Habsyi meninggal dunia tahun 1967 waktu berada di Banjarmasin dan dimakamkan di Turbah Sungai Jingah. Sahabatnya, Habib Muhammad Bin Yahya mendahuluinya 20 tahun sebelum itu dan bermakam di pekuburan Kelambu Kuning, Kutai Tenggarong.